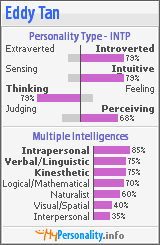Suara ketukan di pintu kantornya membuat Utomo terpaksa menghentikan pembacaan laporan rutin dari berbagai cabang perusahaannya yang bertebaran di meja kerjanya.
“Masuk!” bentak lelaki separuh baya itu sambil melepas kaca matanya dan menggosok kedua matanya dengan punggung tangan.
“Selamat siang, Pak,” seorang gadis yang tampaknya belum terlalu lama meninggalkan masa remaja melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan pelan dan mendekati mejanya. Ia berhenti dekat sekali dengan meja Utomo, berdiri dan menatap lelaki itu dengan tatapan aneh.
“Ada apa, Lis?” Utomo melempar kaca matanya ke atas meja, yang mendarat di atas tumpukan kertas.
“Kenapa Bapak selama ini menghindari saya?”
Itu lagi, desah Utomo. Lelaki itu terhenyak di kursinya, mengusap wajahnya dengan telapak tangan dan mengeluarkan sebuah desahan panjang.
“Saya hanya ingin Bapak …”
“Sudah cukup! Kamu ini ngerti nggak apa yang sudah saya katakan, hah? Gugurkan saja itu! Beres! Kan sudah saya bilang, saya akan beri kamu sepuluh juta untuk membereskan persoalan ini. Kalo uang segitu belum cukup, memangnya kamu mau minta berapa, hah? Kamu mau memeras saya?” Utomo membentak, dan tanpa sadar ia sudah berdiri di tempatnya dan menghantamkan kedua tangannya ke meja.
“Bukan masalah uang Pak, tapi saya tidak mau menggugurkan …”
Dengan gusar Utomo menarik laci mejanya, memasukkan sebundel uang ke dalam sebuah amplop coklat besar dan melemparkannya pada gadis itu, tepat menghantam wajah sang gadis.
“Ambil uang sepuluh juta itu! Ambil! Pokoknya itu cukup buat ngurus perutmu itu! Siapa yang suruh sampai hamil segala? Sekarang, keluar dari tempat ini! Keluar!”
Di bawah tudingan jari Utomo yang terarah ke pintu keluar, gadis itu hanya bisa terisak dan berlalu dari ruangan itu. Amplop berisi uang itu dibiarkannya tergeletak di lantai. Hatinya sakit sekali. Ia keliru menilai Utomo, yang dulu sewaktu berusaha mendekatinya ketika ia baru bekerja beberapa minggu sebagai tenaga administrasi di perusahaan itu, bersikap sangat lembut dan penuh perhatian. Ia terjebak rayuan lelaki setengah baya itu, sampai bersedia ditiduri. Sekarang ia hanya bisa menyesali itu. Nasi sudah jadi bubur. Lisa hanya mampir sebentar ke toilet untuk merapikan diri, mencuci mukanya supaya tidak terlalu tampak habis menangis, dan dengan sekuat tenaga menabahkan hati, pergi meninggalkan kantor itu. Untuk selama-lamanya.
***
Setiap saat rasanya Jim sukar melepaskan bayangan gadis sederhanan itu. Masih muda, tapi sudah harus menjalani hidup dalam kepapaan macam itu. Pemuda itu heran, sekaligus penasaran. Kecantikan macam apa yang ada di balik penampilan kumal itu? Itu mendorongnya mengitari daerah yang ia kira tentu dilewati gadis itu saat bekerja. Tari, nama yang sederhana, meski tidak terkesan kampungan.
“Lo nyari siapa sih, Jim? Dari tadi loe suruh gue muter-muter gak keruan begini?” gerutu Rudi, yang sudah hampir sejam menyetir sedan biru metalik salah satu koleksi Jim.
Jim seperti tidak mendengar gerutuan teman karibnya itu.
Ia tidak henti-hentinya menengok kanan-kiri, terus berusaha untuk bisa melihat seseorang.
“Jim!”
Jim menoleh.
“Sabar dikit, kenapa? Gue masih belum lihat tuh cewek …”
“Cewek yang mana sih yang lagi loe cari? Masak nyari cewek di kawasan pertokoan kayak gini sih? Mahasiswi ato bukan? Kalo mahasiswi, mending kita satronin kampusnya aja. Kan lebih gampang?”
Tiba-tiba Jim menemukan sosok yang dicarinya.
“Itu dia!”
Rudi menghentikan sedan itu, dan berusaha melihat perempuan macam apa yang diburu sohibnya sejak tadi.
“Cewek yang mana sih, kok gue nggak lihat?”
“Itu!”
Rudi mengikuti telunjuk Jim, dan ketika ia melihat sosok yang ditunjuk itu, ia menjadi sangsi.
“Yang mana?”
“Itu!”
Rudi kali ini yakin sosok yang ditunjuk sohibnya itu. Dengan ragu ia bertanya, “Tukang sampah itu?”
Jim mengangguk.
“Astaganaga, Jim … demi dewa Tutatis dan segala jin Kemayoran! Loe kesambet setan mana sih, muter-muter dari tadi cuma buat nyari tukang sam…” Rudi tidak berani melanjutkan kata-katanya karena sekarang Jim sedang menatapnya dengan garang.
“Loe gak usah komentar apa-apa kali ini! Kalo gue butuh komentar loe, seperti biasa, gue bakal ngomong ke elo! Ngerti?”
Rudi menelan ludahnya, bibirnya terasa kering, dan ia tanpa sadar hanya bisa mengangguk kecil. Jim bukan orang yang menyenangkan dan menimbulkan rasa aman kalau ia sedang temperamental seperti itu.
“Lo sana pergi bawa mobil ini! Sejam lagi lo jemput gua di sini, ngerti? Lo boleh puas-puasin keliling kota sama mobil ini.”
Rudi mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Sambil mengangkat bahu, ia masuk ke dalam mobil dan tak sampai lima menit sudah melaju meninggalkan sekepul asap knalpot berbau harumnya premix.
***