Pertama kali melihat sebuah tayangan iklan (maaf) pakaian dalam dimana Tora Sudiro memerankan bapak yang sedang menyupiri mobil berisi keluarganya, saya meringis melihat betapa iklan itu naif sebetulnya dibanding promosi yang lain.
Suasana gerah yang mendera penghuni mobil keluarga itu membuat Tora gelisah. Sampai orang yang duduk di sampingnya, juga anaknya, mengacungkan sebungkus pakaian dalam baru—barang yang sedang dipromosikan oleh iklan itu—untuk dipakai. Maksudnya, supaya Tora bisa merasa lebih adem.
Maka mobil dihentikan, sang Tora meloncat keluar, mencari tempat strategis untuk mengganti (maaf) pakaian dalamnya. Selesai itu, balik lagi ke mobil dengan berseri-seri sambil berujar senang, “Adem! adem!” Padahal seisi mobil melotot kaget …. Memang sih Tora sudah mengganti pakaian dalamnya sehingga merasa lebih nyaman, tapi penonton iklan ini disuguhkan sebuah adegan konyol, dimana ketika mobil itu melaju, di dahan terendah sebuah pohon tempat si Tora mengganti pakaian dalamnya, tergantunglah celana panjang yang tadi ia pakai …….
Tora merasa adem, bukan karena kualitas pakaian dalam itu. Lha, celana panjangnya nggak dipakai, jelas …. (maaf bila bagian ini tidak diteruskan, mengingat ancaman kalo ini melanggar UU Pornografi). Tapi naif bukan, sebuah iklan pakaian dalam, tapi justru menunjukkan bahwa bukan pakaian dalam itu nyatanya yang membuat sang Tora merasa adem.
Tidak punya, malah lebih adem. Ini tentu saja bertentangan dengan cara pandang kebanyakan orang. Punya, tentu saja lebih adem. Coba, punya uang segudang, apa hidup nggak lebih “adem,” lebih nyaman? Punya rumah seperti istana, apa nggak lebih “adem”? Punya ranjang elit yang empuk karena buatan luar negeri, apa nggak lebih “adem”?
Namun, justru saya melihat beberapa kali di pinggir jalan, satu-dua orang pemulung yang tertidur begitu lelap dan damai, hanya di atas rumput, membiarkan gerobak barangnya begitu saja di samping mereka. Tidak ada bangun yang terkejut dan ketakutan kalau-kalau gerobak nafkah mereka dirampok orang. Saya iri melihat rumah bobrok yang tidak punya pengaman rumah macam satpam, alarm atau anjing galak yang makanannya saja lebih mahal daripada yang saya makan sehari-hari. Penghuni rumah-rumah macam itu tidak terbersit sedikit pun ketakutan pada rampok. Di selasar gang kecil di Malang, misalnya, saya mendapati penduduk sederhana yang hidup nyaman dan bahagia. Ibu-ibu yang duduk-duduk mencari kutu atau sekedar menampi beras, anak-anak yang semaksimal mungkin menikmati ruang sesak gang untuk menghamburkan energi Alkaline mereka dengan bermain, para bapak yang sempat muncul untuk makan siang menikmati sebatang rokok sebagai kemewahan yang nikmat.
Mungkin itu, kesederhanaan maksudnya, yang menjadi kebahagiaan kaum monestari pada abad-abad pertengahan, ketika kaul miskin dan hidup amat sederhana menjadi laku hidup mereka sampai mati.
(gimana ya kalo saya lepaskan semua barang saya, hidup mengembara sambil berkotbah, hanya bawa baju dua-tiga setel, Alkitab dan kotak nasi keci serta sebotol air putih, tidur di tempat mana saja yang memungkinkan … wah, mungkin “adem” ya?)
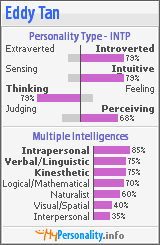


Tidak ada komentar:
Posting Komentar